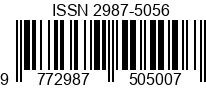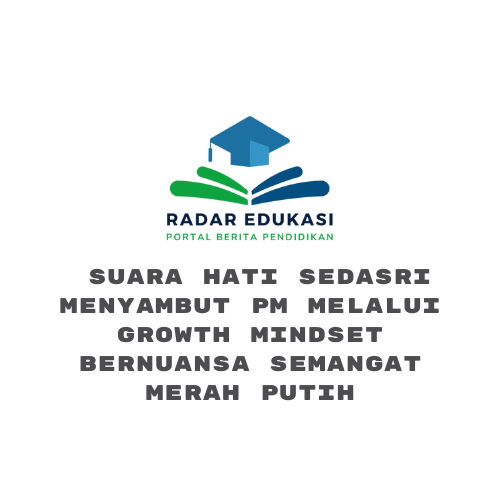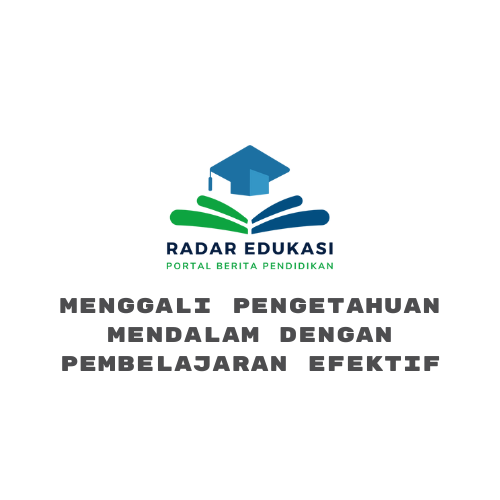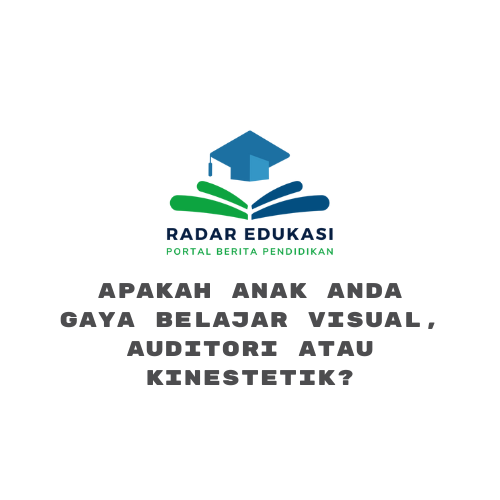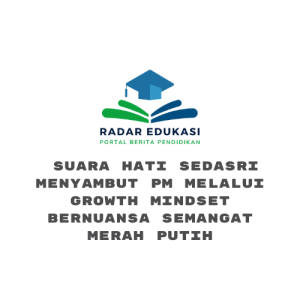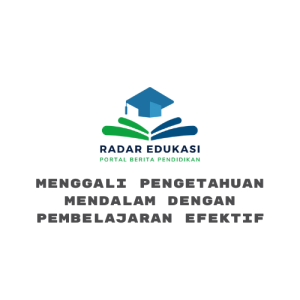BIASWORO ADISUYANTO AKA
Widyaiswara Ahli Utama
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya
biasworoadi.widyaiswara@gmail.com
Dalam sistem demokrasi modern, transparansi menjadi salah satu prinsip kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ia adalah jantung dari akuntabilitas, penegakan etika, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Tanpa transparansi, relasi antara negara dan warganya menjadi kabur, rawan disalahgunakan, dan jauh dari semangat pelayanan. Namun, upaya untuk mewujudkan transparansi dalam tubuh birokrasi bukanlah pekerjaan yang sederhana. Salah satu ancaman paling serius terhadap transparansi adalah konflik kepentingan yang tidak dikenali dan tidak dikelola secara sistematis oleh para penyelenggara negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Konflik kepentingan merupakan titik rawan yang kerap membuka celah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, praktik diskriminatif, bahkan korupsi. Di balik keputusan yang tampak profesional, bisa saja tersembunyi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok yang mengintervensi objektivitas tugas publik. ASN sebagai garda depan pelayanan negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan pelayanan yang mereka jalankan benar-benar bersih dari pengaruh konflik kepentingan. Inilah sebabnya mengapa transparansi ASN tak bisa hanya dibangun dari sistem pelaporan atau publikasi semata, tetapi harus dimulai dari kesadaran dan kemampuan untuk mengenali serta mengelola konflik kepentingan dengan benar.
Secara teoritik, konsep konflik kepentingan dalam administrasi publik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran para ahli etika dan manajemen birokrasi. Wahyudi Kumorotomo dalam Etika Administrasi Negara (2021) menegaskan bahwa konflik kepentingan adalah bagian dari dilema etis birokrasi, di mana nilai-nilai personal kerap bertabrakan dengan prinsip-prinsip objektivitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Ketika ASN tidak mampu menempatkan tanggung jawab publik di atas kepentingan pribadi, maka proses administratif kehilangan legitimasi moralnya. Lebih lanjut, dalam perspektif teori Public Service Ethics, ASN adalah pelayan masyarakat yang bekerja dalam domain kepercayaan (trustee model). Kepercayaan publik terhadap negara dititipkan melalui ASN. Oleh karenanya, segala bentuk intervensi pribadi dalam pengambilan keputusan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah jabatan publik.
Konflik kepentingan bukanlah hal yang abstrak atau jauh dari keseharian birokrasi. Ia bisa muncul dalam bentuk yang sangat kasatmata: seorang pejabat yang terlibat dalam evaluasi proyek di mana adik kandungnya menjadi salah satu kontraktor, atau seorang pegawai yang memberikan kemudahan izin kepada perusahaan milik mantan atasannya. Namun, bentuk konflik kepentingan juga bisa sangat halus dan sulit dideteksi, seperti ketika seorang ASN memiliki saham di sebuah perusahaan yang secara tidak langsung diuntungkan dari kebijakan yang sedang dirancang. Bahkan pemberian hadiah kecil yang berulang dari mitra kerja pun, jika tidak dikendalikan, dapat menimbulkan keberpihakan yang membahayakan integritas tugas publik.
Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap isu konflik kepentingan semakin menguat seiring dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola yang baik (good governance). Pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang menjadi pijakan hukum dalam pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penegasan bahwa setiap pejabat publik wajib menolak pengaruh yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. UU ini bahkan memberikan ruang bagi aparat pengawas internal untuk mengintervensi proses pengambilan keputusan yang dinilai telah terkontaminasi oleh pengaruh pribadi.
Selain itu, perhatian lebih spesifik terhadap perilaku ASN termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa “Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.” Kewajiban menjaga netralitas inilah yang menjadi pagar etis agar ASN tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Netralitas ASN adalah fondasi moral dan hukum agar pelayanan publik tetap bersih dari konflik kepentingan, utamanya dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas.
Guna memberikan panduan teknis yang lebih konkret, Kementerian PAN-RB menerbitkan PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ini tidak hanya menjabarkan definisi dan jenis konflik kepentingan, tetapi juga memuat langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pengendalian secara sistematis. Dalam peraturan ini, seluruh instansi pemerintah didorong untuk membangun sistem identifikasi dini, mencatat kepentingan pribadi ASN, serta menyusun mekanisme pelaporan dan mitigasi yang responsif dan berpihak pada prinsip keterbukaan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi pengelolaan konflik kepentingan masih jauh dari ideal. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Modul Latsar CPNS: Konflik Kepentingan terbitan Lembaga Administrasi Negara (2025), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 2.730 perkara korupsi sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Modul tersebut menegaskan bahwa banyak dari kasus tersebut berakar pada situasi konflik kepentingan yang tidak dikendalikan sejak awal. Data ini memperkuat fakta bahwa konflik kepentingan merupakan akar dari korupsi birokrasi, dan pengelolaannya bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah kerusakan sistemik.
Pengelolaan konflik kepentingan yang efektif mensyaratkan dua hal utama: sistem yang transparan dan individu yang memiliki integritas. Dalam hal sistem, setiap instansi pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pencatatan kepentingan pribadi ASN secara rutin. Pencatatan ini meliputi afiliasi organisasi, keterlibatan dalam bisnis, kepemilikan aset, hingga hubungan kekeluargaan yang mungkin bersinggungan dengan kewenangan jabatan. Proses ini harus dibarengi dengan deklarasi terbuka saat ASN terlibat dalam pengambilan keputusan yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan.
Deklarasi ini menjadi bentuk nyata dari transparansi individual, di mana ASN secara sadar dan jujur mengungkapkan potensi benturan antara tugas jabatan dengan kepentingan pribadi. Tindakan ini bukanlah kelemahan, melainkan wujud dari keberanian moral dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam praktiknya, jika seorang ASN berada dalam posisi konflik kepentingan, pimpinan dapat mengambil langkah pengendalian seperti pengalihan tugas, pembentukan tim independen untuk mengambil keputusan, atau pelimpahan wewenang kepada pihak lain yang netral.
Sementara dari sisi individu, transparansi hanya dapat tumbuh jika integritas menjadi bagian dari budaya kerja. Integritas ASN tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan kerja, keteladanan pimpinan, dan sistem insentif yang berpihak pada perilaku etis. ASN harus diberikan pemahaman bahwa menjaga integritas bukan hanya soal tidak mencuri, tetapi juga soal menjaga jarak yang sehat antara kepentingan pribadi dengan tugas publik. Pelatihan etika, forum diskusi kasus, dan kampanye nilai-nilai integritas perlu terus didorong untuk membangun kesadaran kolektif.
Mengelola konflik kepentingan juga menuntut keberanian institusional. Banyak ASN yang merasa ragu untuk melaporkan potensi konflik karena takut dicurigai, dicap tidak loyal, atau bahkan didiskriminasi. Oleh karena itu, sistem pelaporan harus dirancang ramah, aman, dan melindungi pelapor. Prinsip whistleblowing harus dihidupkan dalam konteks konflik kepentingan, agar ASN merasa aman menyampaikan situasi yang mereka hadapi tanpa khawatir akan dampak negatif bagi karier mereka.
Tentu tidak semua konflik kepentingan dapat dihindari. Dalam struktur sosial yang kompleks seperti Indonesia, hubungan kekerabatan, organisasi sosial, atau afiliasi profesional sering kali tak terelakkan. Yang terpenting bukan semata-mata menghindari seluruh bentuk konflik, tetapi memastikan bahwa saat konflik itu muncul, ASN memiliki keberanian dan sistem pendukung untuk mengelolanya secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Inilah esensi transparansi yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, membangun transparansi ASN bukan sekadar menyusun aturan atau membangun sistem pelaporan elektronik. Transparansi sejati bermula dari integritas individu dan kesadaran moral untuk selalu menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Ketika setiap ASN mampu mengelola konflik kepentingan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab, maka birokrasi Indonesia akan semakin dipercaya, profesional, dan tahan terhadap intervensi kepentingan sempit.
Transparansi bukan hanya alat untuk mencegah korupsi, tetapi juga fondasi untuk membangun pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, langkah pertama dan paling penting dalam mewujudkan transparansi ASN adalah keberanian untuk mengenali dan mengelola konflik kepentingan sejak dini.